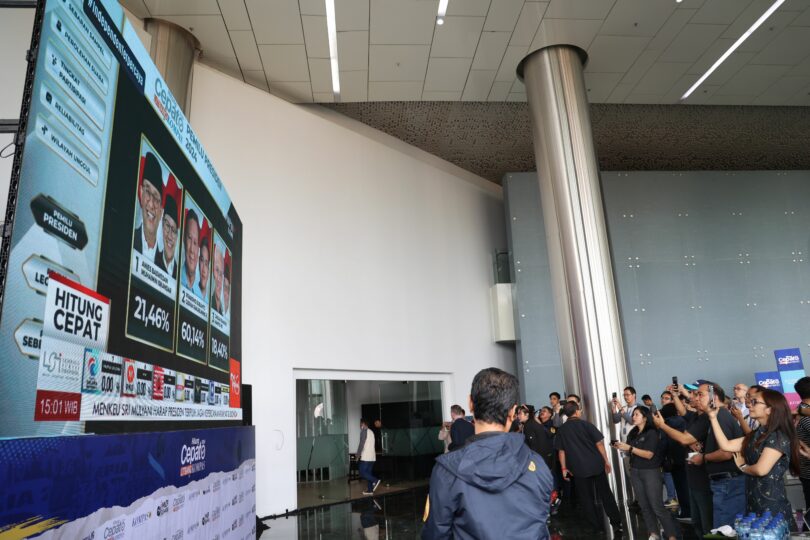Paparan Topik | Pemilihan Umum
Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu
Kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan dalam berbagai lini politik tidak serta merta meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Dunia maskulin dan politik yang kerap diwarnai intrik kecurangan mengakibatkan kaum perempuan enggan terlibat politik.